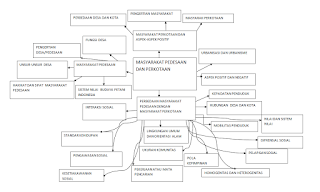1. Masyarakat
Perkotaan dan Aspek- Aspek Positif dan Negatif
A. Pengertian
Masyarakat
Menurut salah satu peneliti
mengatakan bahwa masyarakat
adalah setiap kelompok manusia yang
telaha cukup lama hidup dan bekerjasama, sehingga
mereka ini dapat mengorganisasikan dirinya
berpikir tentang dirinya dalam
satu kesatuan sosial dengan batas-batas tertentu
(R. Linton ).
B. Masyarakat
Pekotaan
Masyarakat perkotaan sering disebut juga urban
community.Pengertian
masyarakat kota lebih ditekankan pada sifat-sifat kehidupannya serta
ciri-ciri kehidupannya yang berbeda dengan masyarakat pedesaan. Perhatian khusus masyarakat
kota tidak terbatas pada aspek-aspek seperti
pakaian, makanan dan peru mahan. tetapi rnempunyai
perhatian lebih luas lagi. Orang-orang kota sudah memandang penggunaan kebutuhan hidup,artinya oleh hanya sekadarnya atau apa adanya. Hal ini disebabkan oleh
karena pandangan warga kota sekitarnya.
C. Perbedaan Desa
dan Kota
Ada beberapa ciri yang dapat dipergunakan sebagai petunjuk untuk
membedakan antara desa dan kota. Ciri
tersebut antara lain :
1) jumlah dan kepadatan penduduk
2) lingkungan hidup
3) mata pencaharian
4) corak kehidupan sosial
5) stratifikasi sosial
6) mobilitas sosial
7) pola interaksi sosial
8) solidaritas sosial dan
9) kedudukan dalam hierarki sistem administrasi nasional
10) mata
pencaharian
2. Hubungan Desa dan Kota
Masyarakat pedesaan dan
perkotaan bukanlah dua komunitas yang terpisah
sama sekali satu sama lain. Bahkan dalam keadaan yang wajar diantara
keduanya terdapat hubungan yang erat, bersifat ketergantungan, karena
di antara mereka
saling membutuhkan. Kota tergantung pada desa dalam
memenuhi kebutuhan warganya akan
bahan-bahan pangan seperti beras, sayur
mayur, daging dan ikan.Desa juga merupakan sumber tenaga kasar bagi jenis
jenis pekerjaan tertentu di
kota, misalnya saja buruh bangunan dalam proyek
proyek perumahan, proyek pembangunan atau perbaikan jalan raya atau
jembatan dan tukang becak.
Sebaliknya, kota menghasilkan
barang-barang yang juga diperlukan oleh
orang desaseperti bahan-bahan pakaian, alat dan
obat-obatan pembasmi hama
pertanian, minyak tanah,obat-obatan untuk memelihara kesehatan dan
alat transportasi. Kota juga menyediakan tenaga-tenaga yang
melayani bidang bidang jasa yang dibutuhkan oleh orang desa tetapi tidak dapat dilakukannya
sendiri, misalnya saja tenaga-tenaga di bidang medis atau kesehatan, montir-montir dll.
3. Aspek Positif
dan Negatif
Perkembangan kota
merupakan manifestasi dari pola kehidupan sosial,
ekonomi, kebudayaan
dan politik. Kesemuanya ini akan dicerminkan dalam
komponen-komponen yang membentukstruktur kota
tersebut. lumlah dan kualitas komponen suatu kota sangat ditentukan oleh tingkatperkembangan
dan pertumbuhan kota tersebut. Secara umum dapat dikenal bahwa suatu
lingkungan perkotaan, terdapat
mengandung 5 unsur yang meliputi :
· Wisma : Unsur ini merupakan bagian ruang kota yang dipergunakan
untuktempat berlindung terhadap alam
sekelilingnya, serta untuk melangsungkan kegiatan-kegiatan sosial
dalam keluarga. Unsur wisma
ini mengharapkan :
1) Dapat mengembangkan daerah peru mahan penduduk yang sesuai
pertambahan kebutuhan penduduk untuk masa mendatang;
2) Memperbaiki keadaan lingkungan perumahan yang telah ada agar
dapat mencapai standar mutu kehidupan yang layak,
dan memberikan
nilai-nilai lingkungan yang aman dan menyenangkan.
· Karya: Unsur ini merupakan syarat yang utama bagi
eksistensi suatu kota, karena unsur ini merupakan jaminan bagi kehidupan bermasyarakat.Penyediaan
lapangan kerja bagi suatu kota dapat dilakukan dengan cara
menyediakan
ruang; misalnya bagi kegiatan perindustrian, perdagangan,
pelabuhan, terminal serta kegiatan-kegiatan kerja lainnya.
· Marga: Unsur ini merupakan ruang perkotaan yang berfungsi untuk
menyelenggarakan
hubungan antara suatu tempat dengan tempat lainnya
di dalam kota (hubungan internal), serta hubungan an tara kota itu dengan
kota-kota atau daerah lainnya (hubungan eksternal).
· Suka: Unsur ini merupakan bagian dari ruang perkantoran untuk
memenuhi kebutuhan penduduk akan fasilitas-fasilitas hiburan, rekreasi,
pertamanan,
kebudayaan dan kesenian.
· Penyempurnaan: Unsur ini merupakan bagian yang penting bagi suatu
kota, tetapi belum secara tepat tercakup
ke dalam ke empat unsur di atas,
termasuk fasilitas keagamaan, pekuburan
kota, fasilitas pendidikan dan
kesehatan, jaringan utilitas umum.
Kota secara internal
pada hakikatnya merupakan satu organisme, yakni
kesatuan integral daritiga
komponen, meliputi "Penduduk, kegiatan usaha
dan wadah" ruang fisiknya. Ketiganya saling
berkait, pengaruh-mempengaruhi, oleh karenanya
suatu pengembangan yang tidak seimbang antaraketiganya,
akan menimbulkan kondisi kota yang tidak positif
Di
pihak lain, kota mempunyai juga peran/fungsi esternal, yakni seberapa
jauh fungsi dan peran kota tersebut dalam kerangka wilayah dan
daerah daerah yang
dilingkupi dan melingkupinya, baikdalam skala regional maupun
nasional.
4. Masyarakat
Pedesaan
A. Pengertian Desa/
Pedesaan
Desa adalah suatu kesatuan hukum di mana bertempat tinggal suatu masyarakat
pemerintahan sendiri. Masyarakat pedesaan ditandai dengan pemilikan ikatan
perasaan batin
yang kuat sesama warga desa, yaitu perasaan setiap warga. Memiliki
ciri – ciri sebagai berikut: 1) Mempunyai pergaulan hidup yang
saling kenai mengenal antara ribuan jiwa.
2) Ada pertalian perasaan yang sarna tentang kesukaan terhadap kebiasaan.
3) Cara berusaha (ekonomi) adalah agraris yang paling umum yang sangat
dipengaruhi alam seperti : iklim, keadaan alam, kekayaan alam, sedangkan
pekerjaan yang bukan agraris adalah bersifat sambilan.
4) di dalam masyarakat pedesaan di antara warganya mempunyai hubungan
yang lebih mendalam dan erat bila dibandingkan dengan masyarakat pedesaan lainnya di luar batas-batas wilayahnya.
5) Sistem kehidupan umumnya
berkelompok dengan dasar kekeluargaan
(Gemeinschaft at au paguyuban).
6) Sebagian besar warga masyarakat pedesaan hidup dari pertanian.
Pekerjaan-
pekerjaan yang bukan pertanian merupakan pekerjaan sambilan
(part time) yang
biasanya sebagai pengisi waktu luang.
7) Masyarakat
tersebut homogen, seperti dalam hal mata pencarian, agama,
adat-istiadat dan sebagainya.
B. Hakikat dan
Sifat Masyarakat Pedesaan
Seperti dikemukakan oleh para ahli atau sumber bahwa masyarakat
Indonesia lebih dari 80% tinggal di pedesaan dengan mata pencarian yang
bersifat agraris.Masyarakat pedesaan yang
agraris biasanya dipandang antara sepintas kilas
dinilai oleh orang-orang kota sebagai masyarakat tentang damai,
harmonis yaitu masyarakat yang adem ayem, sehingga oleh orang kota dianggap sebagai tempat untuk melepaskan lelah dari segala kesibukan,
keramaian dan keruwetan atau kekusutan pikir.
C. Sistem Nilai
Budaya Petani Indonesia
Para ahli disinyalir bahwa di kalangan petani pedesaan ada suatu era
berfikir dan mentalitas yang hidup dan bersifat religio-magis.
Sistem nilai budaya petani Indonesia antara lain sebagai berikut :
1) Para petani di Indonesia terutama di lawan pada dasarnya menganggap
bahwa
hidupnya itu sebagai sesuatu hal yang buruk, penuh dosa,
kesengsaraan.
Tetapi itu tidak berarti bahwa ia harus menghindari hidup
yang nyata dan menghindarkan diri dengan bersembunyi di dalam
kebatinan
atau dengan bertapa, bahkan sebaliknya wajib menyadari
keburukan hidup itu dengan jelas berlaku prihatin dan kemudian sebaik
baiknya dengan penuh usaha atau ikhtiar.
2) Mereka beranggapan bahwa orang bekerja itu untuk hidup, dan kadang
- kadang untuk mencapai
kedudukannya
3) Mereka berorientasi pada masa ini (sekarang), kurang memperdulikan
masa depan, mereka kurang mampu untuk itu. Bahkan kadang-kadang ia
rindu masa
lampau, mengenang kekayaan masa lampau (menanti) datangnya kembali sang ratu adil yang membawa kekayaan bagi mereka).
4) Mereka menganggap alam tidak menakutkan bila ada bencana alam atau
bencanalain itu hanya merupakan sesuatu yang harus wajib diterima
kurang adanya agar peristiwa
-peristiwa macam itu tidak berulang kembali.
Mereka cukup saja dengan menyesuaikan diri dengan alam, kurang adanya
usaha untuk menguasainya.
5) Dan untuk menghadapi alam mereka cukup dengan hidup bergotong
royong,
mereka sadar bahwa dalam hidup itu pada hakikatnya tergantung
kepada sesamanya.
D. Unsur – Unsur
Desa
Daerah, dalam arti tanah-tanah yang
produktif dan yang tidak, beserta
penggunaannya, termasuk juga unsur lokasi,
luas dan batas yang merupakan
lingkungan geografis setempat. Penduduk, adalah hal yang meliputi
jumlah pertambahan, kepadatan, persebaran dan mata pencaharian penduduk desa setempat. Tata kehidupan, dalam hal ini
pola pergaulan dan ikatan-ikatan pergaulan
warga desa. Jadi menyangkut seluk-beluk kehidupan
masyarakat desa (rural
society). Ketiga unsur desa ini tidak lepas satu sama lain, artinya tidak berdiri
sendiri, melainkan merupakan satu kesatuan
Unsur daerah,
penduduk dan tata kehidupan merupakan suatu kesatuan
hidup atau Living unit.
E. Fungsi
Desa
Pertama, dalam hubungannya dengan kota, maka desa yang merupakan hinterland atau daerah dukung berfungsi sebagai suatu daerah
pemberian
bahan makanan pokok seperti padi, jagung, ketela, di samping bahan makanan
lain seperti kacang, kedelai, buah-buahan, dan
bahan makanan lain yang berasal dari hewan.
Kedua, desa ditinjau dari sudut potensi
ekonomi berfungsi sebagai lumbung
bahan mentah (raw material) dan tenaga kerja (man power) yang
tidak kecilartinya.
Ketiga, dari segi
kegiatan kerja (occupation) desa dapat merupakan desa
agraris, desa manufaktur, desa industri, desa nelayan,
dan sebagainya.
5. Urbanisasi
dan Urbanisme
Proses urbansiasi dapat terjadi dengan lambat maupun cepat, hal mana
tergantung daripada keadaan masyarakat yang bersangkutan. Proses tersebut
terjadi dengan menyangkut dua aspek, yaitu :
-perubahannya masyarakat desa menjadi masyarakat kota
-bertambahnya penduduk kota yang
disebabkan oleh mengalirnya penduduk
yang berasal dari
desa-desa (pada umumnya disebabkan karena penduduk
desa merasa tertarik oleh keadaan di kota). Proses urbanisasi boleh dikatakan terjadi diseluruh dunia,baik pada
negara-negara yang sudah maju industrinya maupun yang secara relatif belum
memiliki industri. Bahwa urbanisasi mempunyai akibat-akibat yang negatif
terutama dirasakan oleh negara yang agraris seperti Indonesia ini. Hal ini
terutama disebabkan karena pada umumnya produksi pertanian sangat rendah
apabila dibandingkan dengan jumlah manusia yang dipergunakan dalam
produksi tersebut dan boleh dikatakan bahwa faktor kebanyakan penduduk
dalam suatu daerah over-population merupakan gejala yang umum di negara
agraris yang secara ekonomis masih terbelakang.
6. Perbedaan
Masyarakat Pedesaan dan Masyarakat Perkotaan
Lingkungan umum dan
orientasi terhadap alam
Masyarakat pedesaan berhubungan kuat dengan alam, disebabkan oleh lokasi
geografinya di daerah desa. Mereka sulit mengontrol kenyataan alam yang dihadapinya,
padahal bagi petani realitas alam ini sangat vital dalam menunjang kehidupannya. Tentu akan berbeda
dengan penduduk yang tinggal di kota, yang kehidupannya bebas dari realitas alam,
Misalnya dalam bercocok tanah harus pada waktunya, sehingga ada kecenderungan nerima.
Padahal mata pencaharian juga menentukan relasi dan reaksi sosial.
Pekerjaan atau mata pencarian
Pada umumnya atau kebanyakan mata pencarian daerah pedesaan
adalah bertani. Tetapi mata pencarian berdagang (bidang ekonomi) pekerjaan sekunder
dari pekerjaan yang non pertanian. Sebab beberapa daerah pertanian tidak lepas dari
kegiatan usaha (business) atau industri, demikian pula kegiatan mata pencaharian
keluarga untuk tujuan hidupnya lebih luas lagi.
Ukuran komunitas
Komunitas pedesaan biasanya lebih kecil dari komunitas
perkotaan. Bergantung kepada tipe usaha taninya, tanah yang cukup luasnya sanggup
menampung usaha tani dan usaha ternak sesuai dengan kemampuannya. Oleb sebab itu
komunitas pedesaan lebih kecil daripada komunitas perkotaan.
Kepadatan penduduk
Kepadatan penduduk suatu komunitas kenaikannya berhubungan
dengan klasifikasi dart kota itu sendiri. Contohnya dalam perubahan-perubahan permukiman,
dari penghuni satu keluarga (individual family) menjadi pembangunan multi keluarga
dengan flat dan apartemen seperti yang terjadi di kota.
Homogenitas dan Heterogenitas
Homogenitas atau persamaandalam ciri-ciri sosial dan
psikologis, bahasa, kepercayaan, adat-istiadat. Dan perilaku sering nampak pada
masyarakat pedesaan bila dibandingkan dengan masyarakat perkotaan. Sebagai contoh,
dalam perilaku, dan juga bahasa, penduduk di kota lebih heterogen. Hal ini
Karena daya tarik dari mata pencaharian, pendidikan, komunikasi, dan transportasi,
menyebabkan kola menarik orang-orangdari berbagai kelompok etnis untuk berk
umpul di kola.
Difrensiasi
sosial
Keadaan heterogen dari penduduk kola berindikasi pentingnya
derajat yang tinggididalam diferensiasi sosial. Fasilitas kota, hat-hal yang berguna,
pendidikan, rekreasi, agama, bisnis,dan fasilitas perumahan (tempat tinggal), menyebabkan
terorganisasi-nya berbagai keperluan, adanya pembagian pekerjaan,dan adanya saling
membutuhkan serta sating tergantung. Kenyataan ini bertentangan dengan bagian-bagian
kehidupan di masyarakat pedesaan
Pelapisan
sosial
Klas sosial di dalam masyarakat sering nampak dalam perwujudannya
seperti piramida sosial, yaitu kelas-kelas yang tinggi berada pada posisi atas
piramida, kelas menengah ada di antara kedua tingkat kelas eksterm dari masyarakat.
Mobilitas sosial
Mobilitas sosial berkaitan dengan perpindahan
atau pergerakan suatu kelompok sosial ke kelompok sosial lainnya mobilitas kerja
dari suatu pekerjaan ke pekerjaan lainnya mobiltias teritorial dari daerah desa
ke kota, dari kota ke desa, atau di daerah desa dan kota sendiri.
Interaksi
sosial
Tipe interaksi sosial di desa dan di kota perbedaannya
sangat kontras, baik aspek kualitasnya waupun kuantitasnya
Pengawasan sosial
Tekanan sosial oleh masyarakat di pedesaan lebih kuat
Karena kontaknya yang bersifat pribadi dan ramah-tamah (informal), dan keadaan masyarakatnya
yang homogen.
Pola
kepemimpinan
Aktivitas kerja sama antara sejumlah besar warga masyarakat
desa dalam menyelesaikan sesuatu proyek tertentu bagi kepentingan umum, menjadi
bersifat dipaksakan seperti padat karya. Sifat gotong-royong tidak memerlukan
keahlian khusus. Semua orang dapat mengerjakannya, dan merupakan gejala sosial yang
universal. Inilah yang dikatakan jiwa kebudayaan. Jiwa musyawarah nampak dalam masyarakat
Indonesia Artinya, keputusan suatu rapat seolah-olah merupakan pendirian suatu badan,
di mana pihak mayoritas dan minoritas saling mengurangi pendirian masing-masing,
dekat-mendekati, sehingga barns ada kekuatan atau tokoh yang mendorong proses pencocokkan
dengan dimensi kekuasaan mulai dari persuasi sampai paksaan
Standar
kehidupan
Berbagai alat yang menyenangkan di rumah, keperluan masyarakat,
pendidikan, rekreasi, fasilitas agama, dan fasilitas lain akan membahagiakan
kehidupan bila disediakan dan cukup nyata dirasakan oleh penduduk yang jumlahnya
padat
Kesetiakawanan
sosial
Kesetiakawanan sosial (social solidarity) atau kepaduan
dan kesatuan, pada masyarakat pedesaan dan masyarakat perkotaan banyak
ditentukan oleh masing-masing faktor yang berbeda. Dasarnya justru ketidaksamaan
dan perbendaan pembagian tenaga kerja, saling tergantung, spesialisasi, tidak bersifat
pribadi, dan macam-macam perjanjian serta hubungannya lebih bersifat formal. Pada
masyarakat pedesaan ada istilah sambat. Dalam bahasa Sunda nyambet artinya
minta tolong. Dalam istilah umum.bahasa Indonesia adalah gotong-royong. Aktivitas
ini terlihat dalam menyiapkan pesta atau upacara membangun rumah, perkawinan,
khitanan, atau kematian. Sifatnya lebih otomatis menjaga nama baik keluarga
Nilai
dan sistem nilai
Nilai dan sistem nilai di desa dengan di kola berbeda,
dan dapat diamati dalam kebiasaan, Cara, dan norma yang berlaku. Pada masyarakat
pedesaan, misalnya mengenai nilai-nilai keluarga, dalam masalah pola bergaul dan
mencari jodoh kepala keluarga masih berperan. Nilai-nilai agama masih dipegang kuat
dalam bentuk pendidikan agama (madrasah). Aktivitasnya nampak hidup (fenomenanya).
Bentuk-bentuk ritual agama yang berhubungan dengan kehidupan atau proses mencapai
dewasanya manusia, selalui diikuti dengan upacara-upacara. Nilai-nilai pendidikan
belum merupakan orientasi bernilai penuh bagi penduduk desa, cukup dengan bisa baca-tulis
dan pendidikan agama. Dalam hal nilai-nilai ekonomi, terlihat pada pola usaha
taninya yang masih bersifat subsistem tradisional, kurang berorientasi pada ekonomi.